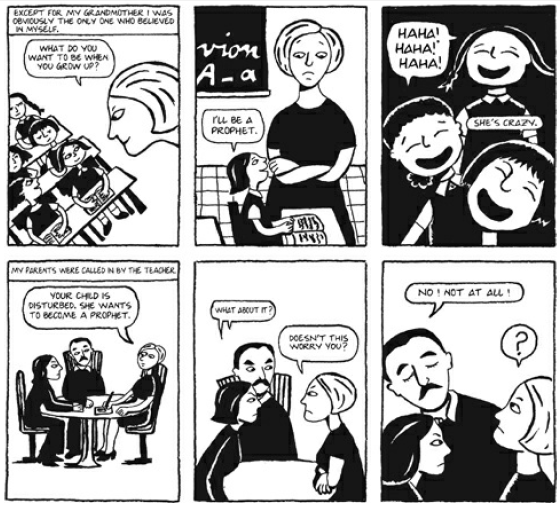|
| Review Buku Goodbye, Things: On Minimalist Living (Hidup Minimalis ala Orang Jepang) by Fumio Sasaki via amazon.com |
Seni hidup minimalis dikenal mulai jadi tren sejak kemunculan Marie Kondo dengan metode Kon Mari-nya. Banyak yang tertarik untuk menerapkan metode Kon Mari apalagi setelah booming buku The Life-Changing Magic of Tidying Up atau Seni Beres-Beres dan Metode Merapikan ala Jepang yang juga ditulis oleh Marie Kondo. Tak hanya itu saja, bahkan Netflix juga memiliki series serupa, yaitu Tidying Up With Marie Kondo.
 |
| Tidying Up With Marie Kondo via Konmari.com |
Nah, berbekal dari adanya pikiran skeptis tentang seni hidup minimalis yang tren, saya jadi penasaran, mengapa metode dari Marie Kondo ini laris dan diterima banyak orang. Oleh karena itu, saya mencoba membaca bukunya dengan meminjam secara gratis di aplikasi Ipusnas. Namun, saya kurang suka membaca buku dari Marie Kondo ini, karena terasa agak mendikte hehe. Oleh karena itu, saya memilih membaca buku Goodbye, Things: Hidup Minimalis ala Orang Jepang dari Fumio Sasaki yang juga terinspirasi dari metode Marie Kondo ini. Saya meminjam buku Goodbye, Things: Hidup Minimalis ala Orang Jepang dari Fumio Sasaki lewat aplikasi Ipusnas, tapi sayangnya cuma ada 1 buku yang tersedia haha, jadi ya harus cepat dibaca biar cepat selesai soalnya sering kehabisan dan akhirnya antri untuk pinjam lagi.
Buku Goodbye, Things: Hidup Minimalis ala Orang Jepang dari Fumio Sasaki dibuka dengan serangkaian gambar atau foto yang menggambarkan potret kehidupan sebelum dan sesudah menerapkan metode hidup minimalis, baik dari yang dialami, atau orang lain yang telah menerapkan metode tersebut.
Kita selalu berpikir dengan memiliki banyak harta benda, maka hidup kita akan semakin bahagia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa, oleh karena itu kita mulai membeli banyak barang dengan alasan, ”Ya siapa tahu butuh” haha. Fumio Sasaki mengungkapkan bahwa dengan adanya pikiran memiliki banyak harta benda akan membuat hidup lebih bahagia, maka kita membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang-barang tersebut. Kemudian, kita mulai menilai orang lain berdasarkan berapa banyak uang yang mereka punya. Kita juga mulai berpikir bahwa uang dapat menyelesaikan sebagian besar masalah kita. Kita dapat memengaruhi pendapat orang lain jika memiliki uang yang lebih banyak, dan jika pendapat orang lain bisa dibeli maka kita yakin akan mendapatkan kebahagiaan. Dan seterusnya.
Fumio Sasaki dalam buku ini menceritakan pengalaman dirinya yang selalu membeli banyak barang untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kebahagiaannya. Ia mengoleksi seperti buku-buku, gitar, serta kamera antik yang ia yakini akan membuatnya terlihat sebagai sosok pria yang memesona. Pada waktu yang sama, Fumio Sasaki juga membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki sesuatu lebih baik dan lebih banyak daripada dirinya. Pada akhirnya, Fumio Sasaki sampai frustasi hingga menyesal menekuni pekerjaan yang dulu ia impikan, berteman dengan alkohol dan putus dengan kekasihnya.
“The things you own, end up owning you”- Tyler Durden, Fight ClubOleh karena itu, Fumio Sasaki mulai membuang dan menjual berbagai barang yang ia koleksi. Ia juga perlahan mulai memahami apa definisi dari bahagia. Setiap orang berhak untuk bahagia, namun memperoleh kebahagiaan dengan cara membelinya hanya akan membuat kita cepat bosan dan rasa bahagia itu tidak tahan lama.
“You’re not your job. You’re not how much money you have in the bank. You’re not the car you drive. You’re not the contents of your wallet. You’re not you f*cking khakis.” – Tyler Durden, Fight ClubMembaca pengalaman Fumio Sasaki, membuat saya teringat dengan diri saya sendiri yang ternyata nggak minimalis-minimalis amat. Saya sering membeli banyak buku namun hanya sedikit yang saya habiskan. Saya berpikir dengan memiliki banyak buku, saya bisa lebih bahagia, karena punya stok banyak bahan bacaan di rumah. Tapi ternyata, kebahagiaan itu hanya terasa sebentar. Suatu saat saya bosan dan tidak tertarik untuk membaca buku yang sudah saya beli tadi. Akhirnya saya membeli buku yang lebih baru lagi dan seterusnya. Selain itu, barang-barang itu juga akan menyita tempat di kamar saya sehingga kamar terasa semakin sempit.
Di buku ini, Fumio Sasaki juga memberikan tips dan cara untuk bijak membuang atau mengurangi barang di rumah kita. Tak hanya itu, manfaat dengan adanya memiliki sedikit barang juga ia jelaskan di buku ini, salah satunya adalah: mudah dan cepat membersihkan kamar atau rumah.
Buku Goodbye, Things: Hidup Minimalis ala Orang Jepang ini saya habiskan dengan waktu relatif cukup singkat, mungkin sekitar 3 hari. Ternyata, Fumio Sasaki juga sering menyelipkan quote dari Tyler Durden di film Fight Club di buku ini hehe. Jadi mungkin saya merasa related dan akhirnya juga tergerak untuk menerapkan gaya hidup minimalis ini.
Tertarik untuk membaca buku Goodbye, Things: Hidup Minimalis ala Orang Jepang dari Fumio Sasaki? Kamu bisa mendapatkannya di toko buku terdekat, atau meminjam di Ipusnas. Selamat membaca!